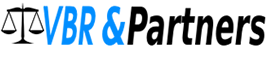TENTANG KAMI
Professional dan berpengalaman
Lebih dari 25 tahun kami berprofesi sebagai pengacara, ribuan kasus hukum yang bervariasi telah kami tangani dengan baik secara profesional
KONSULTASIKAN DENGAN KAMI
Jangan ragu untuk bertanya
Kami siap menjawab
dan membantu kapanpun
anda membutuhkan
Tim kami yang sangat solid selalu siap membantu mempercepat permasalahan hukum anda

VINCENSIUS BINSAR RONNY, S.H., M.H.
Founder, Managing Partner & Lawyer
Menolak Gugatan Perceraian : Hak Konstitusional Pemeluk Agama Katolik
Menolak Gugatan Perceraian : Hak Konstitusional Pemeluk Agama Katolik
Oleh : Vincensius Binsar Ronny S.H., M.H.*
Di tengah meningkatnya angka perceraian di Indonesia, terdapat satu kelompok warga negara yang kerap berada dalam posisi serba salah: pemeluk agama Katolik. Di satu sisi, sistem hukum nasional membuka jalan bagi perceraian melalui Pengadilan Negeri. Di sisi lain, ajaran Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan adalah sakramen yang satu dan tak terceraikan. Ketegangan antara hukum negara dan keyakinan agama ini sering kali berujung pada anggapan keliru bahwa pemeluk Katolik “tidak punya pilihan” ketika digugat cerai. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Hukum Indonesia justru menyediakan ruang yang sah dan konstitusional bagi pihak yang menolak perceraian, termasuk dan terutama berdasarkan keyakinan agama. Penolakan terhadap gugatan cerai bukanlah sikap emosional atau moral belaka, melainkan bagian dari hak hukum warga negara yang dijamin undang-undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan agama pada posisi fundamental. Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih tegas lagi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dengan demikian, sejak awal hukum perkawinan nasional mengakui bahwa nilai-nilai agama bukan sekadar ornamen, melainkan fondasi.
Konsekuensinya Penting: Hakim tidak boleh memandang perceraian semata-mata sebagai urusan administratif atau kehendak sepihak. Perceraian bukan hak absolut yang dapat dituntut tanpa batas. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Frasa “berusaha dan tidak berhasil” sering kali diabaikan, padahal di sanalah inti perlindungan bagi pihak yang menolak perceraian
Ketika seorang Tergugat - khususnya pemeluk Katolik - menyatakan secara tegas penolakannya atas perceraian, sesungguhnya ia sedang mengaktifkan kewajiban hukum hakim untuk memaksimalkan upaya perdamaian. Penolakan tersebut adalah sinyal bahwa ikatan perkawinan belum sepenuhnya runtuh dan bahwa masih terdapat iktikad baik untuk mempertahankannya. Dalam kerangka hukum perdata, ini adalah posisi yang kuat, bukan lemah.
Sayangnya, dalam praktik, gugatan perceraian kerap disusun dengan dalil yang longgar : perselisihan, pertengkaran, atau ketidakharmonisan yang bersifat subjektif. Padahal hukum mensyaratkan bahwa alasan perceraian harus terbukti secara serius dan berkelanjutan. Perselisihan yang bersifat insidental, konflik yang masih mungkin dipulihkan, atau permasalahan yang juga dipicu oleh perilaku Penggugat sendiri tidak serta-merta dapat dijadikan dasar memutus perkawinan.
Di sinilah pentingnya peran pembuktian. Beban untuk membuktikan bahwa perkawinan benar-benar tidak dapat dipertahankan berada pada pihak yang mengajukan gugatan. Tergugat tidak berkewajiban membuktikan bahwa rumah tangganya sempurna; cukup menunjukkan bahwa masih ada harapan dan upaya yang masuk akal untuk memperbaiki relasi. Dalam banyak perkara, justru penolakan aktif dari Tergugat membuka fakta bahwa konflik belum mencapai titik tanpa jalan kembali.
Mediasi, yang sering dipandang sebagai formalitas, seharusnya dimanfaatkan secara strategis. Bagi pemeluk Katolik, mediasi adalah ruang konstitusional untuk menyatakan komitmen mempertahankan perkawinan, menawarkan solusi konkret seperti konseling, pendampingan rohani, atau pengaturan hidup terpisah sementara tanpa bercerai. Jika Penggugat menolak semua opsi ini, catatan tersebut menjadi penting dalam menilai apakah perceraian benar-benar merupakan jalan terakhir.
Perlu pula dipahami bahwa putusan cerai Pengadilan Negeri hanya berdampak pada status perdata, bukan pada status sakramental menurut Gereja. Namun fakta ini tidak berarti negara boleh mengabaikan keyakinan agama pihak yang menolak perceraian. Justru sebaliknya, negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa wajib menunjukkan sensitivitas terhadap keyakinan tersebut dalam proses peradilannya.
Menolak gugatan perceraian bukanlah bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan penggunaan hak hukum secara sah. Ia mencerminkan prinsip bahwa perceraian adalah ultimum remedium - jalan terakhir setelah semua upaya damai gagal. Ketika seorang pemeluk Katolik memilih bertahan dan memperjuangkan perkawinannya di pengadilan, ia tidak sedang melawan arus hukum, melainkan mengingatkan kembali tujuan awal hukum perkawinan itu sendiri, yaitu menjaga keutuhan keluarga
Pada akhirnya, keberanian untuk menolak perceraian adalah keberanian untuk menggunakan hukum secara bermartabat. Ia menegaskan bahwa di balik statistik dan berkas perkara, terdapat keyakinan, komitmen, dan nilai yang patut dihormati oleh negara. Dalam konteks inilah, penolakan terhadap gugatan cerai bukan hanya hak individual, tetapi juga cermin kedewasaan hukum kita dalam merawat pluralitas keyakinan.
Sikap kehati-hatian ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak setiap perselisihan rumah tangga dapat dijadikan dasar perceraian, sepanjang masih terdapat kemungkinan untuk hidup rukun kembali. Bahkan, MA menegaskan bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penggugat untuk menunjukkan bahwa keretakan bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks ini, penolakan perceraian oleh salah satu pihak - terlebih atas dasar keyakinan agama - justru memperkuat kewajiban pengadilan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, bukan sebaliknya.
Berikut beberapa Yurisprudensi yang relevan tentang Penolakan Perceraian:
1. Mahkamah Agung : Perceraian Tidak Bersifat Otomatis
Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung berulang kali menegaskan bahwa perceraian bukan konsekuensi otomatis dari adanya konflik rumah tangga.
“Tidak setiap perselisihan dan pertengkaran suami istri dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan perceraian, sepanjang masih terdapat kemungkinan untuk hidup rukun kembali.”
– Putusan Mahkamah Agung RI (kaidah yurisprudensi perdata keluarga)
Formulasi ini sering digunakan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan cerai tingkat bawah yang terlalu longgar menilai alasan perceraian. Relevansinya bagi pemeluk Katolik yaitu bahwa penolakan cerai justru menunjukkan kemungkinan rukun belum tertutup.
2. Mahkamah Agung : Beban Pembuktian Ada pada Penggugat
Mahkamah Agung juga konsisten menyatakan bahwa pihak yang mengajukan gugatan cerai wajib membuktikan bahwa perkawinan benar-benar tidak dapat dipertahankan.
“Penggugat perceraian harus dapat membuktikan bahwa keretakan rumah tangga telah bersifat permanen dan tidak mungkin dipulihkan.”
– Putusan Mahkamah Agung RI (kaidah hukum tetap)
Yurisprudensi ini penting untuk menolak gugatan yang hanya berisi narasi sepihak, saksi keluarga dekat, atau konflik yang masih insidental.
3. Pengadilan Tinggi : Penolakan Salah Satu Pihak Menguatkan Upaya Damai
Beberapa putusan Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa ketika salah satu pihak secara konsisten menolak perceraian, hakim tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan kegagalan perdamaian.
“Penolakan tergugat terhadap perceraian merupakan indikasi masih adanya iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga upaya perdamaian belum dapat dianggap sia-sia.”
– Putusan Pengadilan Tinggi (dirujuk dalam perkara perceraian perdata)
Yurisprudensi ini sangat relevan bagi pemeluk agama Katolik yang sejak awal menyatakan sikap iman secara tegas.
4. Pengadilan Negeri : Agama sebagai Pertimbangan Substantif
Dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, pertimbangan agama secara eksplisit disebut dalam menilai layak atau tidaknya perceraian.
“Karena para pihak melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya, maka nilai-nilai agama tersebut patut dijadikan pertimbangan dalam menilai permohonan perceraian.”
– Putusan Pengadilan Negeri (praktik yudisial perdata)
Yurisprudensi ini menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bukan norma simbolik, melainkan norma operasional.
*Penulis adalah Advokat, Founder Kantor Hukum VBR & Partners.
Pembagian Harta Bersama yang Berkeadilan bagi Para Pihak
Pembagian Harta Bersama yang Berkeadilan bagi Para Pihak
Oleh : Vincensius Binsar Ronny S.H., M.H.*
Abstrak
Pembagian harta bersama pasca perceraian kerap dipahami secara sederhana sebagai pembagian sama rata antara suami dan istri. Pemahaman tersebut berpotensi mengabaikan keadilan substantif yang merupakan tujuan utama hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembagian harta bersama yang berkeadilan berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyimpangi pembagian 50:50. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak bersifat imperatif harus sama besar, melainkan dapat ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi, itikad baik, dan kepatutan para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan telah memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung.
Kata kunci: harta bersama, keadilan substantif, perceraian, yurisprudensi Mahkamah Agung.
Pendahuluan
Harta bersama (gono-gini) merupakan konsekuensi hukum dari suatu perkawinan yang sah. Dalam praktik, sengketa mengenai harta bersama sering menjadi bagian paling kompleks dalam perkara perceraian, baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum. Tidak jarang, sengketa harta bersama justru berlangsung lebih panjang dan menimbulkan konflik yang lebih tajam dibandingkan sengketa status perkawinan itu sendiri.
Hukum positif Indonesia memberikan pedoman normatif mengenai harta bersama dan pembagiannya. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut secara kaku berpotensi melahirkan ketidakadilan, terutama dalam kondisi di mana kontribusi dan peran para pihak selama perkawinan terbukti tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada keadilan formal, melainkan menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama.
Artikel ini membahas pembagian harta bersama yang berkeadilan dengan menitikberatkan pada kerangka normatif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara nyata menyimpangi pembagian 50:50.
Pembahasan
Kerangka Normatif Pembagian Harta Bersama
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini menegaskan adanya persatuan harta yang lahir dari ikatan perkawinan, tanpa membedakan siapa pihak yang secara langsung memperoleh harta tersebut.
Selanjutnya, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini sering dipahami sebagai dasar pembagian sama rata antara para pihak.
Namun demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menyatakan bahwa pembagian harta bersama harus selalu dilakukan secara sama besar dalam segala keadaan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut patut dipahami sebagai prinsip umum yang penerapannya harus mempertimbangkan tujuan hukum, yakni keadilan dan kepatutan.
Keadilan Substantif sebagai Dasar Pembagian
Keadilan substantif menghendaki agar pembagian harta bersama tidak semata-mata didasarkan pada persamaan matematis, melainkan pada penilaian yang proporsional terhadap fakta konkret. Kontribusi para pihak dalam perkawinan tidak selalu identik, baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi.
Kontribusi non-ekonomi, seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan moral, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan dan pemeliharaan harta bersama. Namun, apabila terbukti bahwa salah satu pihak sama sekali tidak menjalankan kewajiban rumah tangga, tidak beritikad baik, atau bahkan merugikan keluarga, maka pembagian yang sama rata patut dipertanyakan dari sudut keadilan substantif.
Dengan demikian, keadilan substantif memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara komprehensif kontribusi, perilaku, dan kepatutan para pihak sebelum menentukan proporsi pembagian harta bersama.
Yurisprudensi Mahkamah Agung yang Menyimpangi Pembagian 50:50
Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembagian harta bersama tidak bersifat mutlak harus sama rata. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/AG/1995, Mahkamah mempertimbangkan bahwa apabila salah satu pihak terbukti tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga secara patut dan tidak memberikan kontribusi terhadap pembentukan harta bersama, maka pembagian yang tidak sama besar merupakan pilihan yang adil dan beralasan hukum.
Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/1998 menegaskan bahwa ketentuan pembagian masing-masing separuh bukanlah norma imperatif yang mengikat secara kaku. Hakim dibenarkan menyimpangi pembagian tersebut sepanjang didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan keadilan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 kembali menegaskan prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa asas keadilan dan kepatutan dapat mengesampingkan pembagian matematis apabila kontribusi para pihak terhadap perolehan harta bersama terbukti tidak seimbang. Putusan ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menempatkan keadilan substantif sebagai dasar utama pembagian harta bersama.
Rangkaian yurisprudensi tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi hakim tingkat pertama dan banding untuk menerapkan pembagian harta bersama secara proporsional sesuai dengan fakta konkret perkara.
Penutup
Pembagian harta bersama yang berkeadilan bukanlah pembagian yang selalu sama besar, melainkan pembagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi, itikad baik, dan kepatutan para pihak. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka normatif, sementara yurisprudensi Mahkamah Agung membuka ruang yang jelas bagi penyimpangan dari pembagian 50:50 demi tercapainya keadilan substantif.
Dengan pendekatan demikian, pembagian harta bersama tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis dalam putusan pengadilan.
*Penulis adalah Advokat, Founder Kantor Hukum VBR & Partners.
Terimakasih bang... Akhirnya status perkawinan saya yang digantung istri saya selama 2 tahun beres juga. Mantab
Terimakasih Bang atas bantuannya selama ini, next time kalo ada apa-apa lagi terkait masalah legal, saya ga bakal cari orang lain dan pasti datang ke abang untuk handle masalah ini
Saya acungi jempol tentang profesionalisme kerja timnya dalam menangani kasus saya